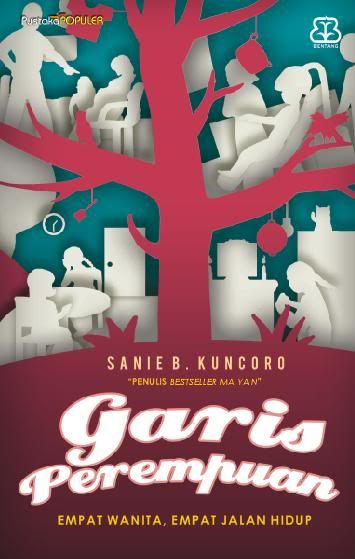
Judul Buku: Garis Perempuan
Penulis: Sanie B. Kuncoro
Tebal: x+378 hlm; 20,5 cm
Cetakan: 1, Januari 2010
Penerbit: Bentang
Empat Perawan Menguak Takdir
Setiap perempuan adalah perawan. Sudah jalannya seorang perempuan menjadi perawan. Kecuali meninggal sebelum mendapatkan haid, seorang perempuan akan atau pernah menjadi perawan. Itulah yang tergambar sebagai titik tolak utama novel perdana pengarang perempuan berpseudonim Sanie B. Kuncoro ini.
Lebih
lanjut Sanie mengungkapkan, bahwa keperawanan adalah milik berharga
seorang perempuan. Kepada siapa yang punya keperawanan akan
mempersembahkan selaput daranya, merupakan hak prerogatifnya. Tidak ada
yang bisa menentukan, termasuk orang yang melahirkannya. Kecuali,
tentu saja, nasib. Itulah yang menjadi modal utama novel bertajuk Garis Perempuan ini.
Adalah empat orang perawan, iniren dan congkouren,
yang menjalin persahabatan sejak belia. Ranting, putri seorang janda
penjual karak (kerupuk beras); Gendhing, anak dari pasutri buruh cuci
dan tukang becak; Tawangsri, anak gadis seorang pedagang batik yang
bersuamikan seorang lelaki yang tidak bisa diandalkan; Zhang Mey, gadis
Tionghoa yang memiliki ayah seorang pengusaha dan ibu juragan becak.
Meski
sehati, mereka memiliki nasib yang berbeda. Ranting, terlahir dalam
kemiskinan dan tanpa ayah berhenti sekolah sebelum lulus SMA dan
menggantikan ibunya yang sakit sebagai penjual karak. Ketidakmampuan
mereka membayar biaya operasi penyakit yang kian parah memperhadapkan
Ranting pada pilihan sulit: membiarkan ibunya meninggal atau
menyerahkan keperawanannya kepada lelaki setengah baya yang menawarkan
pelunasan biaya rumah sakit dan rumah yang lebih layak selaku istri
ketiga. Ia pun menyerahkan dirinya pada apa yang ia percaya sebagai
takdir. "Mungkin inilah cara Tuhan berbelas kasihan
kepadaku. Tidak ingin dilihat-Nya aku sengsara menjajakan karak
selamanya dan ingin diberikan-Nya kehidupan yang lebih baik dengan
menjadi istri juragan. Bahwa kehidupan yang lebih baik secara financial
itu kuperoleh dengan menjadi istri ketiga, barangkali memang begitulah
takdirku," katanya (hlm. 86, dengan sedikit koreksi).
Namun, setelah keperawanan ia persembahkan di ranjang perkawinan
kepada lelaki separuh baya yang tidak ia cintai, ia berubah pandangan, "Aku tidak mau menjadi istri Basudewo selamanya. Terlalu murah hargaku kalau harus kuberikan seluruh hidupku kepadanya." (hlm. 96).
Nasib
Gendhing sedikit lebih lumayan dari Ranting. Namun, meskipun masih
berorangtua lengkap dan lulus SMA, ia tidak bisa menjangkau impiannya
dari lembar halaman iklan Koran. Beruntung, ia bisa bekerja di salon
milik majikan ibunya sambil menunggu pekerjaan lain yang sesuai dengan
harapannya. Sebagai perempuan yang disebut-sebut memancarkan naraiswara
(cahaya rahasia yang dipancarkan Ken Dedes), Gendhing berusaha
mengelak dari godaan para lelaki pesolek yang mengunjungi salon.
Sayangnya, nasib menyingkapkan takdirnya: ia bukan ratu atau dewi,
tetapi prajurit yang memiliki kekuatan melaksanakan tugas yang
dibebankan padanya dan mempertaruhkan dirinya atas nama kesetiaan.
Ketika ibunya bertindak ceroboh dan terlilit utang, Gendhing
memutuskan, "Aku tidak akan menjadikan diriku sebagai
perempuan lain bagi seorang laki-laki, dengan atau tidak berdasarkan
perkawinan yang sah. Yang kulakukan ini adalah transaksi. Cukup satu
kali kulakukan, dia ambil perawanku, kuterima uangnya, lalu selesai." Gendhing
pun pasang harga pada seorang lelaki separuh baya kesepian setelah
meyakinkan dirinya bahwa komodifikasi tubuh yang akan ia lakukan
adalah, "…. Politik keperawanan, mengeksplorasi darah
perawan demi sebuah timbal balik yang berdaya guna untuk kehidupan yang
lebih baik, secara ekonomi." (hlm. 198).
Baik
Ranting maupun Gendhing mengorbankan hak prerogatifnya demi untuk
menyelamatkan keluarga dari masalah yang lebih besar lagi.
Tidak
demikian nasib kedua sahabat mereka yang lain, Tawangsri dan Zhang
Mey. Kedua perawan ini bisa lulus SMA dan memasuki perguruan tinggi
karena ditopang kemampuan finansial yang memadai. Bagi mereka, walau
tidak sepenuhnya, ada keleluasaan untuk mempersembahkan keperawanan
kepada lelaki yang mereka inginkan.
Ketika bertemu dengan seorang lelaki yang mampu memuaskan kerinduannya akan kasih sayang ayahnya, dan setelah melewati pembicaraan mengenai keperawanan dengan lelaki tersebut, Tawangsri memutuskan, "Akan
kupergunakan hak pilihku untuk menentukan siapa laki-laki pertamaku.
Sama seperti seorang laki-laki memilih perempuan pertamanya. Tidak ada
keharusan bagiku untuk tetap menjadi perawan demi sebuah pernikahan.
Menjadi tetap perawan atau tidak adalah suatu pilihan dan aku hanya akan
melakukannya dengan seseorang yang kuinginkan, dengan atau tanpa
pernikahan." (hlm.274). Namun, ketika gayung bersambut, apakah
lelaki itu akan memperoleh keperawanan Tawangsri yang menurutnya bagai
mitos?
Sampai
mengenal lelaki idamannya, Zhang Mey dibayang-bayangi tradisi
saputangan yang harus ia lewati sebagai perawan Tionghoa. Ketika ia
menikah dengan laki-laki yang dikenan keluarga, ibu mertuanya akan
menyiapkan saputangan putih untuk menampung darah perawannya. Sungguh
bukanlah yang Zhang Mey harapkan, karena ia memiliki pilihan lain,
seorang lelaki berlainan etnis yang mencintainya. Seorang
laki-laki yang tidak masuk perhitungan orangtuanya untuk menjadi
penerima keperawanan anak perempuan mereka. Pada puncak
ketakberdayaannya, Zhang Mey berujar, "… aku akan
melaksanakan kewajibanku, menjalani tradisi atas nama kehormatan
keluarga, menjadi pengantin yang perawan bagi seorang laki-laki yang
terpilih sebagai suamiku pada masa nanti." (hlm. 351)
Topik keperawanan sudah pasti bukanlah hal yang baru dalam dunia fiksi Indonesia. Namun, Garis Perempuan
memiliki berbagai kelebihan sebagai sebuah fiksi tentang keperawanan.
Berbicara mengenai keperawanan (dan mempersembahkan keperawanan), mau
tidak mau, akan mengarah pada perbincangan aktivitas seksual. Sebagai perempuan, boleh dikatakan, Sanie B. Kuncoro
adalah pencerita yang terkendali. Kendati terbuka peluang baginya
untuk mengeksplorasi seksualitas secara lebih gamblang, Sanie tidak
mengambil pilihan ini. Hal ini mengindikasikan bahwa meski mengangkat tema seks, semua pengarang pasti memiliki filter. Dalam hal ini, tidak ada istilah munafik ataupun dilakukan demi sesuatu yang disebut 'seni'. Bagi pembaca dewasa –dan novel ini memang untuk pembaca dewasa, yang tidak eksplisit pun sudah bisa dipahami.
Berbekal
sekian tahun menulis fiksi, memproduksi rangkaian kalimat cantik tidak
menjadi kesulitan bagi Sanie. Penulisannya yang cenderung puitis
sekalipun menjabarkan tragedi memberikan daya tarik yang emosional.
Sanie memiliki kekayaan diksi dan kekuatan metafora yang tidak selalu
bisa didapatkan dari pengarang perempuan lain dalam ranah olah kata
fiksi Indonesia. Meskipun harus diakui bahwa
kerap kekayaan diksi yang ditampilkan Sanie dalam berbagai dialog
kurang realistis. Karakter yang berbicara terasa janggal untuk bermain
kata-kata canggih. Akibatnya, sangat terasa jika para karakter ini terlepas dari perwatakan dan latar yang sesungguhnya telah dirancang dengan unggul.
Garis Perempuan
sudah jelas bukanlah novel dengan satu konflik yang kompak. Novel
beralur lurus ini adalah bagai empat novelet yang dikolaborasi menjadi satu.
Kisah hidup keempat perawan yang berusaha menguak takdir masing-masing
ini dibentangkan satu demi satu dalam bagian-bagian yang judulnya
menggunakan nama-nama mereka. Tidak ada yang mengikat konflik mereka
menjadi satu; kecuali bahwa mereka sama-sama perempuan yang menjalani
kehidupan perawan dan menjalin persahabatan yang erat. Namun, ini
bukanlah kelemahan dan sama sekali tidak mengganggu kenikmatan membaca.
Latar
budaya lokasi berlangsungnya novel ini harus dikukuhkan sebagai salah
satu kekuatan yang tidak bisa diabaikan dari Sanie. Sanie jelas
menguasai budaya Jawa dan Tionghoa yang menjadi akar keempat tokoh
novelnya termasuk perbedaan yang hingga saat ini masih menjadi
kesenjangan antar kedua budaya. Pembaca yang bukan Jawa dan bukan
Tionghoa tidak akan kebingungan walau terdapat percakapan dalam kedua
bahasa itu. Sanie memberikan artinya secara langsung dan menyediakan
glosarium untuk 'kata-kata sulit' ini.
Akhirnya,
sehubungan dengan problem mengenai keperawanan, yang memperhadapkan
perempuan pada makhluk bernama laki-laki, secara arif Sanie
menyampaikan bahwa memang ada laki-laki yang memandang bahwa
keperawanan adalah sesuatu yang secara mutlak berhak didapatkannya,
tetapi ada juga laki-laki, seperti Tenggar (hlm. 351) yang bisa berkata
kepada perempuan yang ia cintai, "Ketika
kau bersama seorang nanti, akan kuanggap kau hanyalah tersesat. Entah
berapa lama ketersesatanmu, kenanganmu terhadapku akan membawamu kembali
padaku".














0 comments:
Post a Comment